Luwu – Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertambangan menjadi tulang punggung bagi banyak wilayah di Indonesia. Mulai dari batubara, nikel hingga emas, kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi tampak menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat dan pendapatan negara. Namun, di balik janji manis itu, kerusakan lingkungan yang ditinggalkan tak bisa diabaikan.
Pertambangan, terutama yang dilakukan secara terbuka dan masif, telah menyebabkan deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya habitat satwa liar. Banyak sungai tercemar limbah logam berat, menyebabkan kerusakan ekosistem dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekitar.
Di sisi lain, masyarakat lokal kerap hanya menjadi penonton dari kekayaan alam yang dikeruk di tanah mereka sendiri. Lapangan kerja yang dijanjikan tak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Bahkan, konflik sosial dan penggusuran paksa pun kerap mewarnai operasi tambang di berbagai daerah.
Pemerintah memang telah mengatur melalui undang-undang dan perizinan, namun penegakan hukum sering kali lemah. Tambang ilegal menjamur, dan tambang legal pun kerap luput dari pengawasan ketat. Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan: apakah pertambangan masih layak dijadikan tulang punggung ekonomi jika konsekuensinya adalah kerusakan jangka panjang yang tak bisa diperbaiki?
Solusi tentu bukan menutup tambang secara total, melainkan mengelola dengan pendekatan yang berkelanjutan. Investasi pada teknologi ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan transparansi dalam perizinan menjadi langkah awal. Selain itu, perlu ada keberanian politik untuk menindak tegas pelanggaran, tak peduli seberapa besar pengaruh korporasi tambang.
Tambang bukan musuh, namun tanpa pengelolaan yang bijak, ia bisa menjadi bencana. Kini saatnya memilih: mengeruk kekayaan hari ini dan meninggalkan kerusakan untuk generasi esok, atau membangun masa depan yang adil dan lestari.
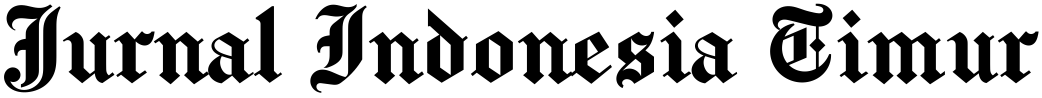
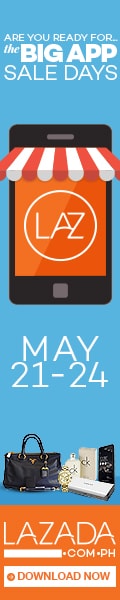

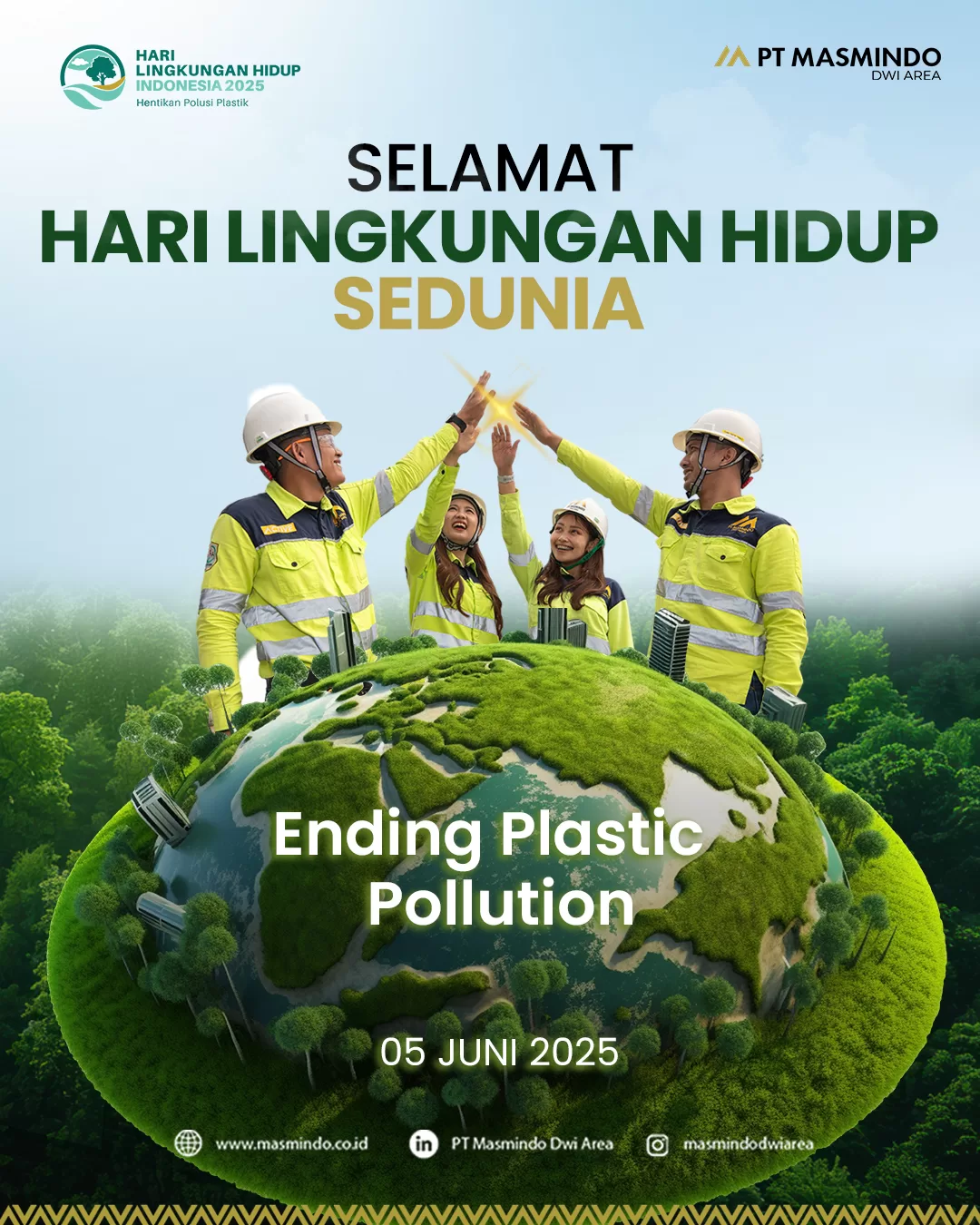









Komentar